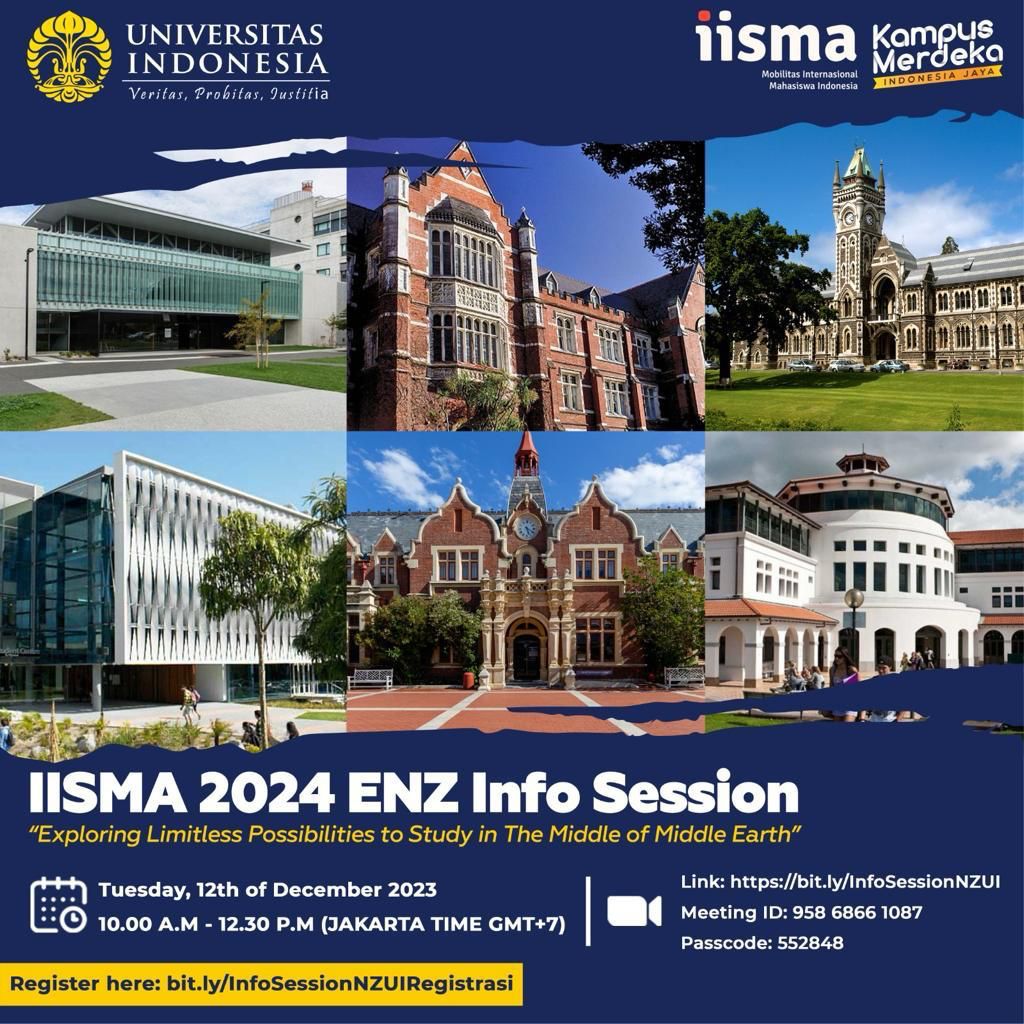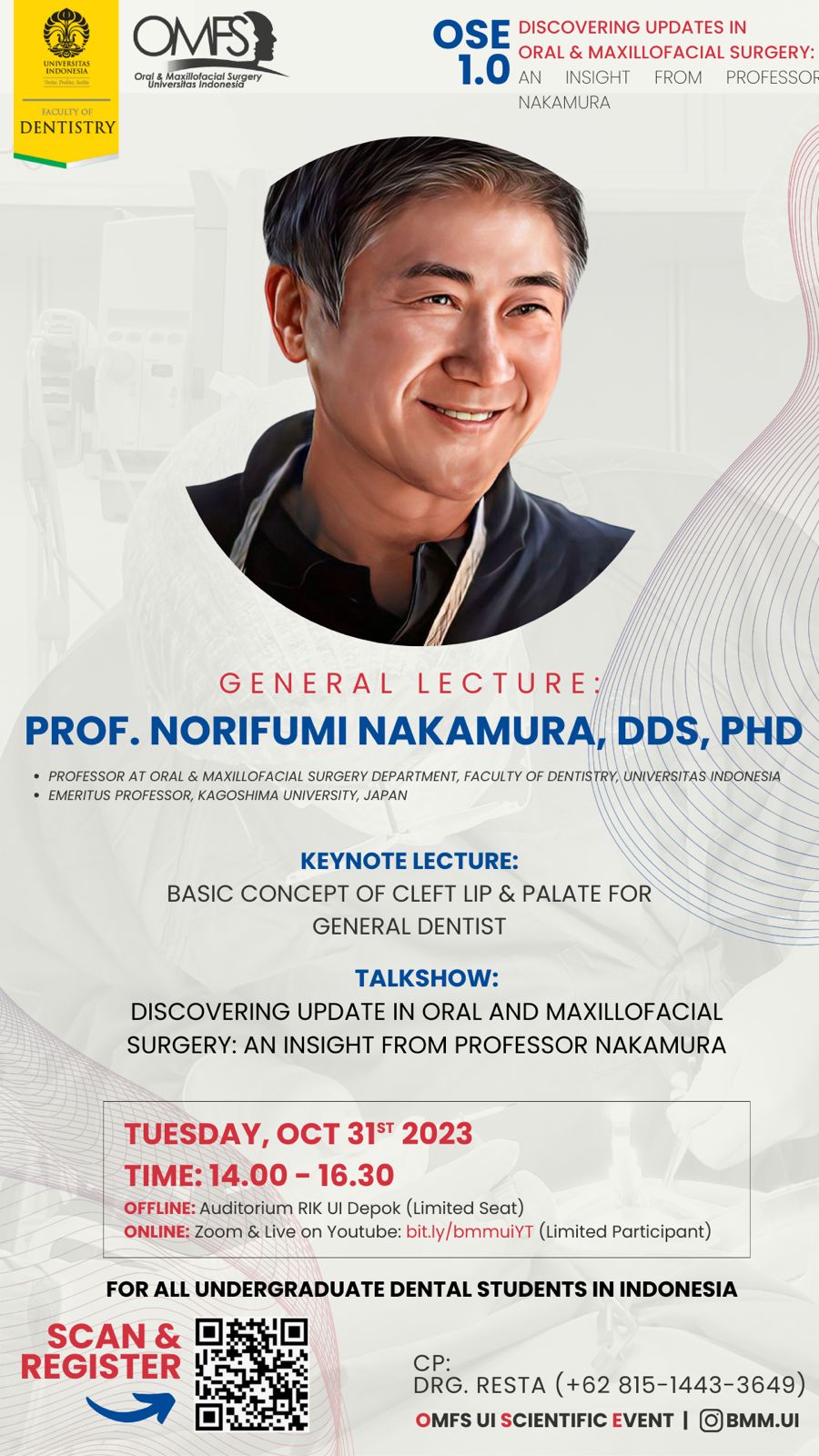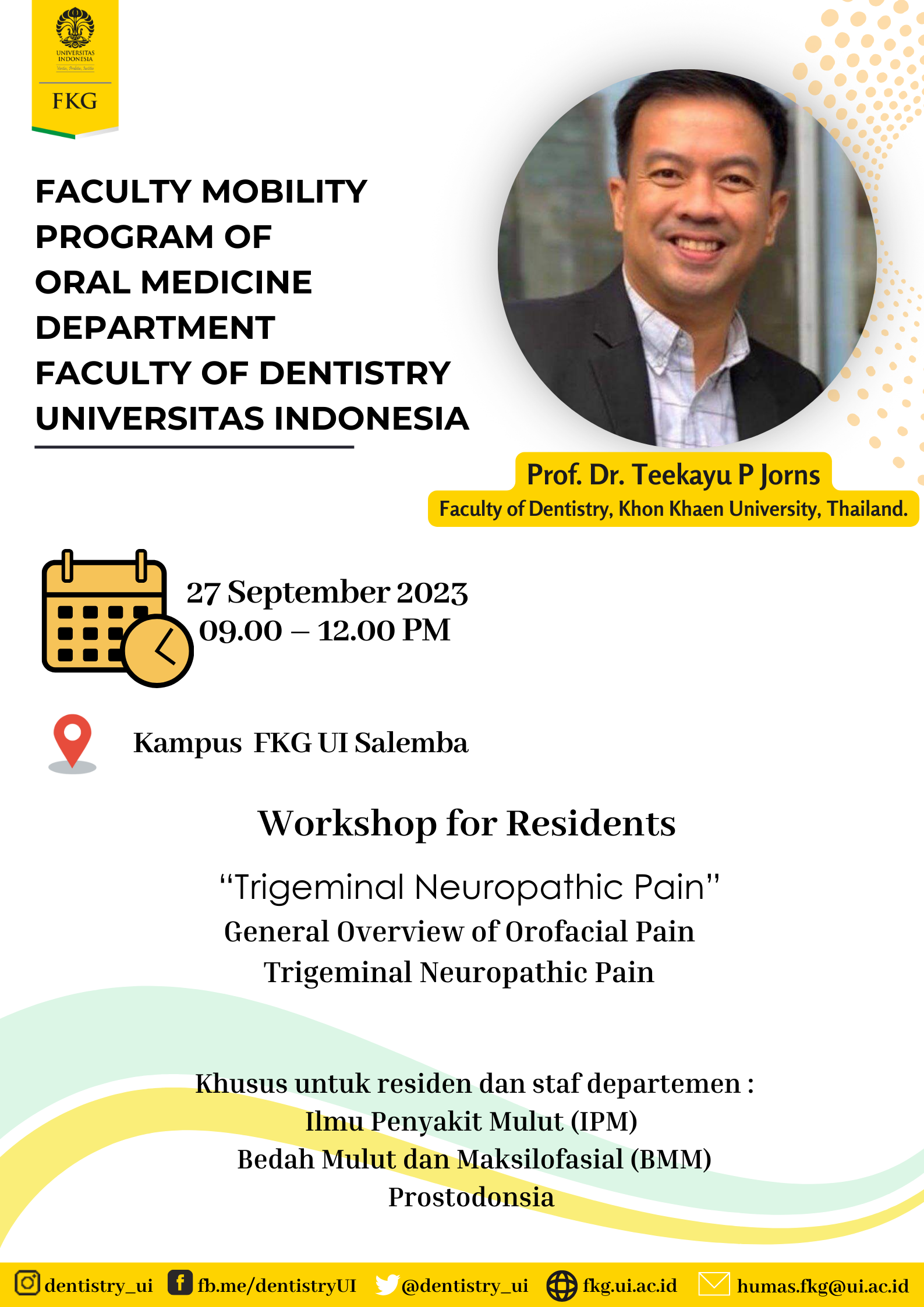Penerimaan Mahasiswa Baru
Penerimaan Mahasiswa Baru
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia untuk semua program studi pada jenjang sarjana, profesi dokter gigi, magister, dokter gigi spesialis dan doktoral.
Program Studi